
Oleh: Santi Susanti
Ibu Rumah Tangga
Indonesia sedang berada dalam krisis lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan data IMF yang melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara peringkat 1 dengan tingkat pengangguran tinggi se-ASEAN pada tahun 2024. Semakin banyak lulusan Universitas (sarjana dan diploma) di Indonesia justru masuk dalam lingkaran pengangguran.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data yang mencemaskan. Bahwa pada 2014, jumlah penganggur bergelar sarjana tercatat sebanyak 495.143 orang. Angka ini melonjak drastis menjadi 981.203 orang pada tahun 2020, dan meskipun sempat turun menjadi 842.378 orang di tahun 2024, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi. (CNBC.co.id 01/05/2025)
Akibat sulitnya mendapat pekerjaan, banyak tenaga kerja lulusan perguruan tinggi seperti diploma dan sarjana terpaksa banting setir menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, bahkan office boy (pramu kantor). Ini dilakukan demi bertahan hidup ditengah minimnya lapangan kerja di sektor formal dan badai pemutusan hubungan kerja dalam beberapa tahun terakhir.
Seperti dijelaskan oleh Ihlazul Amal (pramu kantor), meskipun ia bergelar Sarjana Ilmu Komputer. Ia harus rela bekerja tidak sesuai dengan keahlian komputer yang sudah dipelajari selama 5 tahun di Unikom karena sangat sulit mendapat pekerjaan, sehingga dengan terpaksa harus bekerja sebagai pramu kantor yang kebetulan hanya itu saja posisi yang sedang kosong di perusahaan tersebut. (BBC.co.id 01/05/2025)
Hal senada juga disampaikan oleh Heru, sopir mobil rental. Heru adalah Sarjana Teknik Mesin lulusan tahun 2023. Ia pun harus rela menjadi sopir, walaupun ia sebenarnya kecewa karena merasa sayang, perjuangan menempuh pendidikan Sarjana sangat sulit karena menghabiskan waktu dan biaya. Tetapi karena sudah kebutuhan dan mencari pekerjaan sangat sulit, dengan berat hati ia pun harus rela menjadi sopir rental mobil. (BBC.co.id 01/05/2025 )
Pendidikan vokasional (kejuruan) atau diploma memang lebih menekankan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Banyak perusahaan lebih suka merekrut talenta yang siap pakai daripada lulusan sarjana yang butuh waktu adaptasi.
Kurikulum Perguruan tinggi masih banyak yang belum responsif terhadap perubahan dunia kerja. Kondisi antara kampus dan industri juga kerap lemah. Sementara itu, kewirausahaan belum menjadi budaya kuat dikalangan mahasiswa.
Fakta bahwa gelar sarjana tidak otomatis menjamin pekerjaan untuk saat ini adalah sebuah realita yang sesungguhnya. Maka untuk keluar dari krisis ini, perubahan harus dimulai dari hulu.
Ini semua adalah buah dari penerapan sistem kapitalis. Dan masalah pengangguran memang masih menjadi PR besar bagi pemerintah di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Padahal, pengangguran berkorelasi positif dengan kemiskinan. Sedangkan kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu berbagai kerawanan sosial, sekaligus menjadi indikator minimnya tingkat kesejahteraan.
Berbagai jurus pun sudah dilakukan. Namun, tampaknya, dari rezim ke rezim pengangguran terus jadi problem warisan dan sulit dientaskan, bahkan hingga sekarang. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi makro dunia yang makin hari makin tidak karuan.
Walhasil, lapangan kerja yang sudah sempit makin sulit didapat. Bahkan, tsunami PHK terjadi di mana-mana.
Masalahnya, selama ini pemerintah hanya fokus pada aspek pasokan atau supply tenaga kerja, bukan pada demand, yakni menciptakan lapangan kerja. Pendidikan vokasional digenjot sedemikian rupa di tengah penerapan paradigma kurikulum merdeka. Itupun lebih fokus di level SMK dengan konsep apa adanya.
Begitu pun dengan pendidikan vokasional. Pada faktanya, pendidikan berorientasi kebidangan ini tidak serta merta terserap oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Penyebabnya ditengarai kurikulum yang ada tidak link and match dengan kebutuhan DUDIKA ini. Selain dinilai teoretis, juga berbasis pada target menciptakan tenaga kerja kuli tidak berdaya saing tinggi.
Namun, jika melihat data jenis pekerjaan yang diakses oleh para pekerja, wajar jika bekerja tidak otomatis sejahtera. Nyatanya mayoritas (59,31 persen) pekerja Indonesia bergelut dalam jenis pekerjaan informal. Padahal pekerja informal sering kali dikategorikan sebagai pekerja rentan. Selain rata-rata memiliki pendapatan yang rendah dan tidak stabil, mereka pun tidak memiliki jaminan perlindungan, termasuk layanan kesehatan dasar.
Wajar jika semua jurus yang diandalkan pemerintah ini tidak bisa diharapkan mengentaskan problem pengangguran yang berkelanjutan dengan problem kemiskinan. Padahal, ke depan, jumlah kemiskinan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan makin maraknya PHK, disertai fluktuasi harga sejumlah bahan pokok yang menambah beban ekonomi masyarakat.
Sayangnya, evaluasi atas kebijakan yang dilakukan tidak pernah sampai pada akar permasalahan. Terkait pendidikan vokasional, narasi yang muncul hanya wacana reaktualisasi kurikulum pelajaran. Begitu pun dengan program Kartu Prakerja. Evaluasinya, hanya soal perbaikan teknis saja.
Betul bahwa kemampuan atau kompetensi merupakan bagian penting dari kualitas dan daya saing sumber daya manusia atau tenaga kerja. Namun, yang jadi problem terbesar maraknya pengangguran yang berdampak pada minimnya kesejahteraan hari ini adalah sempitnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja serta buruknya atmosfer untuk berusaha.
Saat ini, pemerintah sangat bergantung pada proyek-proyek pembangunan yang berbasis investasi asing serta sektor ekonomi non-riil. Padahal, investasi asing berbasis pada utang ribawi kerap memprioritaskan menyerap tenaga asing. Sedangkan, pembangunan sektor ekonomi non-riil hanya memacu pertumbuhan ekonomi di atas kertas, bahkan menyedot kekayaan rakyat ke tangan segelintir konglomerat.
Di pihak lain, situasi perekonomian pun sangat dipengaruhi oleh kondisi internasional. Hal ini merupakan konsekuensi penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang menjadikan Indonesia tidak memiliki kemandirian dan kedaulatan. Peran negara dalam sistem ini pun hanya sebatas regulator. Bahkan, negara tidak jarang berkolaborasi dengan kekuatan modal untuk memeras keringat rakyatnya.
Wajar jika aset-aset kekayaan alam yang sejatinya melimpah ruah, tidak bisa dimiliki sepenuhnya untuk modal menyejahterakan rakyat. Kebijakan ekonomi bahkan politiknya disetir dan diarahkan oleh kekuatan kapitalisme global. Kekuasaan oligarki demikian mencengkeram hingga situasi ekonomi pun sangat rentan dipermainkan oleh kepentingan negara-negara besar.
Menciptakan lapangan kerja dan ruang berusaha yang kondusif semestinya menjadi prioritas kebijakan politik ekonomi negara sebesar Indonesia. Selain merupakan salah satu negeri terpadat di dunia, dengan jumlah penduduk sangat besar, mencapai 273,52 juta jiwa (per Januari 2024), proporsi angkatan mudanya pun sangat besar.
Sayangnya, selama ini pemerintah hanya berhenti di retorika saja. Paradigma kapitalisme yang dikukuhi negara membuat penguasa gamang untuk memihak rakyatnya. Alih-alih berusaha menyejahterakan, penguasa kerap menzalimi rakyatnya dengan kebijakan yang menyengsarakan. Mulai dari pajak, kapitalisasi layanan publik, undang-undang proasing, termasuk proyek investasi yang membuka tenaga asing, dan sebagainya.
Islam Menjawab
Berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme, dalam Islam, pemimpin atau negara menempatkan diri sebagai pengurus dan penjaga. Adanya dimensi akhirat pada kepemimpinan Islam membuat seorang penguasa akan takut jika zalim dan tidak adil kepada rakyat. Mereka akan berusaha maksimal mengurus dan menyejahterakan rakyat dengan jalan menerapkan syariat Islam sebagai tuntunan kehidupan.
Ajaran Islam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dimulai dari mewajibkan seorang laki-laki untuk bekerja. Namun, hal ini tentu butuh support system dari negara, berupa sistem pendidikan yang memadai sehingga seluruh rakyat khususnya laki-laki memiliki kepribadian Islam yang baik sekaligus skill yang mumpuni.
Pada saat yang sama, negara pun wajib menyediakan lapangan kerja yang halal serta suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk berusaha. Caranya tidak lain dengan membuka akses luas kepada sumber-sumber ekonomi yang halal, dan mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang, apalagi asing. Termasuk mencegah berkembangnya sektor non-riil yang kerap membuat mandek, bahkan menghancurkan perekonomian negara.
Sektor-sektor yang potensinya sangat besar, seperti pertanian, industri, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan sejenisnya akan digarap secara serius dan sesuai dengan aturan Islam. Pembangunan dan pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara sesuai dengan potensinya.
Negara akan menerapkan politik industri yang bertumpu pada pengembangan industri berat. Hal ini akan mendorong perkembangan industri-industri lainnya hingga mampu menyerap ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah ruah dengan kompetensi yang tidak diragukan sebagai output sistem pendidikan Islam.
Negara pun dimungkinkan untuk memberi bantuan modal dan memberi keahlian kepada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, mereka yang lemah atau tidak mampu bekerja akan diberi santunan oleh negara hingga mereka pun bisa tetap meraih kesejahteraan.
Layanan publik dipermudah, bahkan digratiskan sehingga apa pun pekerjaannya tidak menghalangi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, bahkan hidup secara layak. Dengan begitu, kualitas SDM pun akan meningkat dan siap berkontribusi bagi kebaikan umat.
Semua ini kembali pada soal paradigma kepemimpinan Islam yang berperan sebagai pengurus dan penjaga. Seorang pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang dipimpinnya. Jika ada satu saja rakyat yang menderita karena buruknya pengurusan mereka, pemimpin harus siap-siap menerima azab Allah ﷻ.
Karena dalam Islam, negara adalah raa'in (pengurus rakyat). Sehingga dalam penerapan sistem Islam negara tidak berlepas tangan, penguasa akan menjamin kesejahteraan dan membuka lapangan kerja.
Wallahu a'lam bi ashshawaab
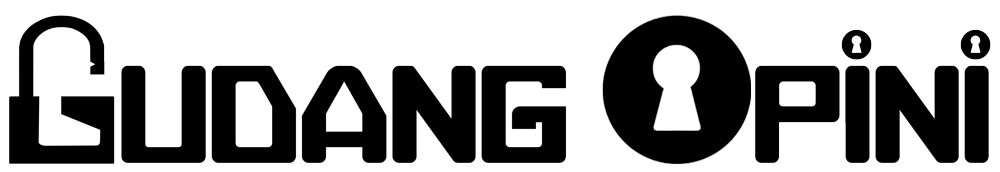









0 Komentar