
Oleh: Muhar
Sahabat Gudang Opini
Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sebagai negara berpendapatan menengah atas, data dan fakta justru menunjukkan hal sebaliknya.
Bank Dunia (World Bank) mengungkap, di tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yakni US$ 6,85 per kapita per hari (PPP 2017).
Bank Dunia mencatat, jumlah masyarakat Indonesia mencapai 285,1 juta penduduk. Artinya, sekitar 171,8 juta warga Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Data ini didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan kemiskinan pendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar US$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari (kurs Rp 16.800/US$).
Sedangkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dengan garis kemiskinan nasional perkapita Rp 595.242 perbulan, tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, atau hanya sekitar 24,06 juta jiwa.
Sementara itu, Ekonom dan Mahasiswa Doktoral di Universitas Indonesia mengatakan, perbedaan antara data BPS dan Bank Dunia bukan terletak pada sumber data, melainkan pada metode penghitungan dan standar hidup yang digunakan. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan pada angka US$ 6,85 per hari untuk negara yang masuk dalam kategori berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, sementara BPS menggunakan standar sekitar Rp20.000 per hari.
Dipo pun berpendapat bahwa garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS mungkin terlalu rendah dan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini dapat memberikan gambaran yang menyesatkan tentang kondisi sebenarnya.
Dipo juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik yang efektif. Ia menunjukkan adanya kebingungan dalam definisi kemiskinan di Indonesia dan mendesak agar diterapkan standar yang konsisten, agar perbandingan dengan negara lain menjadi lebih relevan. (theconversation.com)
Masalah Struktural Kapitalisme
Ironisnya, kemiskinan ini juga berjalan beriringan dengan ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Laporan Global Inequality Report 2022 menempatkan Indonesia di posisi keenam negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia. Empat orang terkaya memiliki kekayaan lebih besar dari gabungan kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Laporan Oxfam 2023 bahkan menunjukkan bahwa kesenjangan ini tumbuh lebih cepat dibanding negara Asia Tenggara lainnya.
Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia bukan semata akibat kemalasan dan kelemahan individu, tetapi merupakan masalah struktural dari sistem yang diterapkan, yakni kapitalisme. Kapitalisme membuka peluang akumulasi kekayaan secara massif oleh segelintir elit. Sumber daya publik dikapitalisasi; sektor strategis seperti energi, air dan pertambangan didominasi oleh korporasi. Negara, alih-alih menjadi pelayan rakyat, justru sering bertindak sebagai fasilitator kepentingan pasar.
Kebijakan pencabutan subsidi, liberalisasi sektor vital, serta privatisasi aset publik menjadi bukti nyata peran negara yang menjauh dari rakyat. Sementara itu, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi kemewahan yang susah dijangkau bagi jutaan warga miskin.
Dengan logika sederhana, Pengamat Ekonomi dan Sosial Kota Tangerang Selatan, Mukti Al Mansur menyatakan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi pada banyak orang yang tidak mampu memenuhi/mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun telah berusaha semaksimal mungkin. Jadi bukan karena faktor individu semata yang malas maupun lemah tidak mampu mencari nafkah.
"Sudah mencari tapi enggak dapat (mencukupi kebutuhannya), artinya sudah struktural ini kondisinya," terangnya melalui Podcast bertajuk "Solusi Islam Tuntaskan Kemiskinan" yang tayang di kanal YouTube Lisan, pada Kamis (15/5/2025).
Standar Kemiskinan dalam Islam
Islam tidak hanya memandang kemiskinan dari aspek materi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (dharûriyyat) dengan cara yang menjaga martabat dan keimanan seseorang.
Dalam al-Quran, orang miskin disebut dengan istilah faqir dan miskin. Dalam pandangan para ulama, kedua istilah ini memiliki makna berbeda, namun kadang saling dipertukarkan. Keduanya disebutkan sebagai penerima zakat, sebagaimana firman Allah ﷻ:
اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ
"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan..." (QS. at-Taubah [9]: 60).
Menurut Imam Ibn Katsir dalam ayat di atas orang faqir didahulukan karena jauh lebih membutuhkan daripada yang lainnya. Namun, menurut Abu Hanifah, orang miskin kondisinya jauh lebih buruk daripada orang faqir (Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur'ân al-‘Azhîm, 4/165).
Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam "Kitab Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah" (hlm.142-143) secara lebih rinci menjelaskan: Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Karena itu siapa saja yang penghasilannya lebih sedikit dari kebutuhan pokoknya, ia tergolong fakir, dan halal bagi dia menerima zakat. Ia boleh diberi zakat sampai kadar yang dapat mengangkat kefakirannya dan mencukupkan kebutuhannya (Zallum, Al-Amwâl, hlm. 142).
Adapun miskin adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, seakan-akan kefakiran telah "memukimkan" mereka (tidak bisa bergerak), namun mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا
"Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap, atau sebutir dua butir kurma." Para sahabat bertanya, "Kalau begitu, seperti apakah orang yang miskin itu?" Beliau menjawab: "Orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadaannya itu tidak diketahui orang supaya orang bersedekah padanya, dan tidak pula meminta-minta ke sana ke mari." (HR. Muslim no. 1722).
Dengan demikian, menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, miskin tingkatannya di bawah fakir, sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:
اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍۗ
"atau orang miskin yang sangat fakir." (QS. al-Balad [90]: 16).
Maksudnya, orang yang bergelimang debu karena tak punya pakaian dan kelaparan. Orang miskin berhak menerima zakat dan boleh diberi sampai kadar yang mengangkat kemiskinannya dan mencukupi kebutuhannya (Zallum, Al-Amwâl, hlm. 143).
Ini menegaskan bahwa kefaqiran dan kemiskinan diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup.
Keadilan Sistem Ekonomi Islam
Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah keadilan (al-‘adl). Keadilan dalam Islam bukan hanya bersifat moral, melainkan merupakan pilar dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan ekonomi, mekanisme distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian. Islam menolak sistem yang membuat harta beredar hanya di sekelompok orang kaya (QS al-Hasyr [59]:7).
Islam juga menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan secara merata dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pemerataan kekayaan di tengah-tengah masyarakat ini membutuhkan peran negara. Dalam Islam, negara bukanlah aktor pasif atau sekadar regulator seperti dalam sistem kapitalisme. Negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu (pangan, sandang dan papan; juga pendidikan dan kesehatan).
Hal ini ditegaskan oleh Al-Maliki dalam kitabnya, Politik Ekonomi Islam (2001). Beliau menyebut bahwa Negara Islam (Khilafah) wajib mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan rakyat dan mencegah pemusatan kekayaan di tangan segelintir individu atau korporasi.
Karena itu Al-Maliki (2001) menegaskan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam pembangunan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perdagangan dan industri. Keterlibatan negara dalam sektor-sektor ini menjadi sangat penting.
Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan
Dalam mengentaskan kemiskinan, Islam memiliki sejumlah mekanisme. Di antaranya:
Pertama, pengaturan kepemilikan yang adil. Islam mengatur kepemilikan harta untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Al-Quran menyatakan:
كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ
"Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian," (QS. al-Hasyr [59]: 7).
Karena itu dalam sistem Islam, SDA (sumber daya alam) seperti minyak, gas, tambang dan mineral adalah milik umum (al-milkiyyah al-‘aammah) yang wajib dikelola hanya oleh negara untuk rakyat. Haram dikuasai oleh individu atau korporasi.
Namun, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini telah memperlihatkan sisi gelapnya melalui praktik eksploitasi ekonomi yang terjadi akibat liberalisasi pasar dan privatisasi sumber daya alam.
Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan dan pengelolaan aset-aset strategis seperti minyak, gas, air dan hutan diserahkan kepada individu atau korporasi.
Akibatnya, yang terjadi adalah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara masyarakat luas justru kehilangan akses terhadap hak-hak ekonominya. Ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang menempatkan sumber daya strategis sebagai milik umum.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (2004) dalam An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm menegaskan bahwa negara berkewajiban mengelola dan mendistribusikan hasil dari sumber daya tersebut demi kemaslahatan umat. Prinsip kepemilikan umum ini bertujuan mencegah eksploitasi serta menjamin distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata.
Kedua, dalam Islam, mekanisme seperti zakat, infak dan sedekah juga memastikan redistribusi dan pemerataan kekayaan di tengah-tengah masyarakat.
Ketiga, dalam Islam, setiap lelaki dewasa, terutama yang punya tanggungan keluarga, wajib mencari nafkah. Ini karena al-Quran memerintahkan:
لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ
"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya," (QS. ath-Thalaq [65]: 7).
Menurut Imam Ibn Katsir, ayat ini memerintahkan individu untuk memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kapasitasnya (Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur'ân al-‘Azhîm, 10/45–48).
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً اِسْتِعْفَافًا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ، وَتَعَطُفًا عَلَى جَارِهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ
"Siapa saja yang mencari dunia (harta) dengan cara yang halal karena menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dan untuk membantu tetangganya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama." (HR al-Baihaqi).
Di sisi lain, agar setiap orang yang wajib bekerja bisa mendapatkan pekerjaan, maka negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi warganya melalui kebijakan ekonomi berorientasi sektor riil seperti perdagangan, pertanian dan industri.
Keempat, jaminan kebutuhan dasar oleh negara. Negara dalam Islam wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (pangan, sandang dan papan). Negara juga wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi warganya. Ini karena pemimpin negara (Imam/Khalifah) dalam Islam bertanggung jawab penuh atas urusan warga negaranya. Rasulullah ﷺ bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR an-Nasa’i).
Semua mekanisme ini hanya mungkin dilakukan jika negara menerapkan syariah Islam secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang seharusnya diwujudkan, khususnya di negeri ini.
Kritik Pembatasan Kelahiran
Di tengah kegagalan kapitalisme mengentaskan kemiskinan, muncul solusi semu seperti pembatasan kelahiran. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, misalnya, sempat mewacanakan syarat vasektomi bagi warga miskin penerima bansos.
Meskipun kemudian diklarifikasi bahwa kebijakan tersebut bersifat opsional dan tidak hanya melalui vasektomi, wacana tersebut menunjukkan kesalahan arah berpikir dalam melihat akar masalah kemiskinan.
Padahal, Islam mengharamkan praktik vasektomi dan kebiri, karena merusak fungsi reproduksi secara permanen. Nabi ﷺ melarang praktik kebiri, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas (HR al-Bukhari).
Selain itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan memiliki banyak keturunan, sebagai bagian dari sunnah Rasulullah ﷺ (HR Ahmad).
Pembatasan kelahiran (tahdîd an-nasl) hukumnya haram, terlebih jika menjadi program negara. Namun, pengaturan kelahiran (tanzhîm an-nasl) yang bersifat sementara dan sukarela dibolehkan, seperti dengan alasan kesehatan ibu atau jarak antar kelahiran.
Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia adalah buah dari sistem kapitalisme yang rakus dan eksploitatif. Solusi yang ditawarkan kapitalisme, seperti pembatasan kelahiran, tidak menyentuh akar masalah, bahkan malah menambah kezaliman baru.
WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.
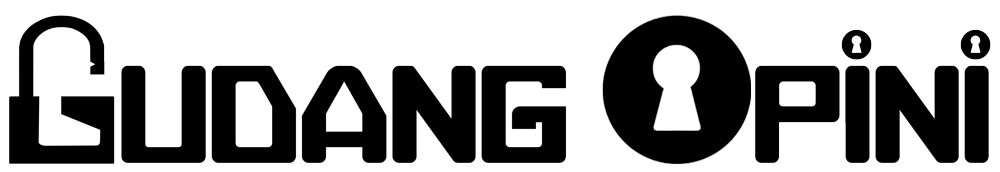









0 Komentar